Oleh Laurensius Bagus
(Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Cokroaminoto Yogyakarta)
Di Manggarai Barat, kain songke bukan sekadar kain tenun. Ia adalah bahasa diam yang diwariskan turun-temurun, berbicara tentang identitas, martabat, dan penghormatan terhadap leluhur. Dalam setiap helai benang hitam, merah, dan putih yang berpadu di tangan perempuan penenun, tersimpan kisah panjang tentang kehidupan orang Manggarai: kisah tentang tanah, kerja keras, dan kehormatan adat. Namun di zaman digital ini, songke sedang menghadapi perubahan besar. Ia tak lagi hanya berfungsi di dalam rumah adat atau upacara, tetapi kini menembus pasar global dan layar gawai. Dari alat tenun sederhana di kolong rumah, songke kini tampil di panggung mode dan media sosial, menjadi simbol antara adat, pasar, dan gengsi.
Dulu, lipa songke hanya dikenakan pada momen sakral: pernikahan, ritual adat, atau penyambutan tamu kehormatan. Setiap motif mengandung makna. Warna hitam melambangkan tanah, merah melambangkan keberanian, dan putih melambangkan kemurnian niat. Motif golo (gunung) melukiskan kampung sebagai pusat kehidupan, wae (air) melambangkan sumber kesuburan, ai (pohon) melambangkan kehidupan dan keteduhan, sementara garis-garis yang tersusun rapi melambangkan keteraturan dan keseimbangan hidup. Setiap orang yang mengenakan songke tahu bahwa ia tidak sekadar memakai kain, melainkan sedang membawa identitas dan harga diri keluarga. Dalam upacara penti atau barong wae, songke dikenakan dengan penuh hormat, menjadi simbol kesatuan antara manusia, alam, dan roh leluhur.
Namun waktu telah berubah. Dunia yang dulu berjalan perlahan kini bergerak cepat. Gawai, media sosial, dan pasar digital membawa lipa songke ke ruang-ruang baru yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Di kota Labuan Bajo, songke kini bukan hanya kain adat, tetapi juga busana kasual yang dipadukan dengan celana jeans atau blazer. Di media sosial, anak muda Manggarai dengan bangga berpose memakai songke di pantai atau kafe. Para perajin dan penenun pun mulai memasarkan hasil karya mereka melalui Instagram, TikTok, dan marketplace. Dari sisi ekonomi, ini tentu menggembirakan: songke kini memberi penghasilan tambahan, bahkan menjadi sumber ekonomi utama bagi banyak keluarga.
Namun di balik kemajuan itu, muncul pertanyaan yang tak bisa diabaikan: apakah nilai budaya songke ikut berubah? Apakah makna sakralnya mulai tergeser oleh nilai pasar dan gengsi modern?
Sebagian orang tua di kampung merasa khawatir. Mereka melihat anak-anak muda mengenakan songke tanpa tahu arti motif di dalamnya. Songke kini lebih sering dilihat sebagai pelengkap gaya atau simbol status sosial, bukan lagi tanda kehormatan. Dalam pesta modern, orang memakai songke untuk tampil menawan, bukan karena panggilan budaya. Nilai kesakralan yang dulu begitu dijaga perlahan terkikis oleh kebutuhan pasar dan selera mode.
Namun, di sisi lain, perubahan ini juga menghadirkan peluang baru. Songke yang dulu hanya dikenal di kampung-kampung Manggarai kini melintasi batas daerah dan bahkan negara. Di pameran budaya di Jakarta atau Bali, songke tampil sebagai karya seni tinggi. Para desainer lokal mulai menggabungkan motif songke dalam busana modern, memperkenalkan budaya Manggarai ke dunia luar. Beberapa kelompok perempuan di kampung seperti di Todo, Cibal, atau Ruteng bahkan berinisiatif membentuk koperasi tenun, memasarkan produk mereka ke wisatawan Labuan Bajo. Mereka tak hanya menjual kain, tapi juga menjual cerita — tentang tangan-tangan yang sabar, tentang leluhur yang dihormati, dan tentang identitas yang tetap dijaga meski zaman berubah.
Perubahan ini ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, lipa songke mengalami modernisasi: ia dikenal luas, dihargai secara ekonomi, dan menjadi kebanggaan baru. Tapi di sisi lain, ia berisiko kehilangan nilai filosofisnya. Di sinilah tantangan besar masyarakat Manggarai hari ini — bagaimana menjaga makna budaya di tengah arus komersialisasi yang deras. Kain songke tidak boleh menjadi sekadar komoditas tanpa jiwa. Ia harus tetap menjadi simbol kebersamaan, kerja keras, dan kesetiaan pada akar budaya.
Menjaga nilai songke berarti menjaga cara berpikir. Artinya, ketika generasi muda memproduksi atau mengenakan songke, mereka perlu tahu kisah di baliknya: tentang tangan ibu yang menenun di sore hari sambil menjaga anak, tentang doa yang diucap di awal tenunan, tentang hubungan manusia dengan alam. Pemahaman ini penting agar modernisasi tidak menjauhkan masyarakat dari akar budayanya sendiri. Sebab, bila songke hanya dilihat dari sisi ekonomi, maka yang hilang bukan sekadar makna, tapi juga jiwa budaya Manggarai itu sendiri.
Meski begitu, kita juga tak bisa menolak arus perubahan. Dunia digital telah membuka ruang baru bagi pelestarian budaya. Banyak komunitas kini memanfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan proses menenun, mengajarkan motif kepada generasi muda lewat video, dan mempromosikan hasil karya penenun ke luar negeri. Ini cara baru untuk bertahan — cara yang menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu menjadi musuh budaya, selama ia digunakan dengan kesadaran dan rasa hormat. Di sinilah pentingnya keseimbangan antara adat dan zaman.
Di tengah benturan antara pasar dan adat, muncul fenomena menarik: songke menjadi simbol gengsi baru. Orang memakai songke bukan karena kewajiban adat, tapi karena kebanggaan. Ini perubahan yang paradoksal, tapi juga positif bila dimaknai dengan bijak. Ketika seseorang mengenakan songke di kota besar, sesungguhnya ia sedang mengumumkan identitasnya: bahwa ia berasal dari tanah yang kaya budaya, dari orang-orang yang tahu menghargai kerja keras dan kesabaran. Songke menjadi bentuk ekspresi diri sekaligus pernyataan eksistensi budaya.
Pergeseran makna ini tidak perlu ditakuti, selama ada kesadaran kolektif untuk menjaga akar budaya. Perempuan penenun di Manggarai hari ini bukan hanya pengrajin, tapi juga pendidik budaya. Di tangan mereka, songke tetap menjadi ruang untuk berbicara tanpa kata — tentang cinta pada tanah, pada leluhur, dan pada kehidupan yang dijalani dengan tabah. Di sisi lain, generasi muda yang mempromosikan songke lewat media sosial juga ikut menenun nilai-nilai baru: nilai kebanggaan dan keberlanjutan.
Perjumpaan antara adat dan pasar ini sebenarnya mencerminkan dinamika kebudayaan itu sendiri. Budaya tidak beku; ia hidup, berubah, dan menyesuaikan diri dengan zaman. Yang penting bukan menolak perubahan, tapi memastikan bahwa setiap perubahan tetap berpijak pada nilai dasar: penghormatan terhadap manusia dan alam. Songke akan tetap menjadi “bahasa tanpa kata” orang Manggarai selama ia dibuat dan dikenakan dengan niat yang tulus dan penghargaan pada nilai-nilai lama.
Pada akhirnya, lipa songke bukan hanya kain yang menutupi tubuh, tetapi simbol yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Dari tangan perempuan yang menenun di desa, hingga remaja yang memamerkannya di media sosial, songke terus menuturkan cerita tentang siapa orang Manggarai sebenarnya. Di tengah zaman digital yang serba cepat, ia mengingatkan kita bahwa keindahan sejati lahir dari kesabaran, ketulusan, dan rasa hormat terhadap warisan budaya.
Mungkin kini songke tak lagi seberapa sakral seperti dulu, tapi justru di situlah kekuatan barunya. Ia mampu hidup di antara dua dunia: dunia adat yang penuh makna dan dunia modern yang penuh peluang. Selama orang Manggarai masih menenun, mengenakan, dan menghargai lipa songke dengan hati yang jujur, maka benang-benang itu akan terus bercerita — tentang adat, tentang pasar, dan tentang gengsi yang menemukan keseimbangannya dalam satu kain yang penuh makna.(*)

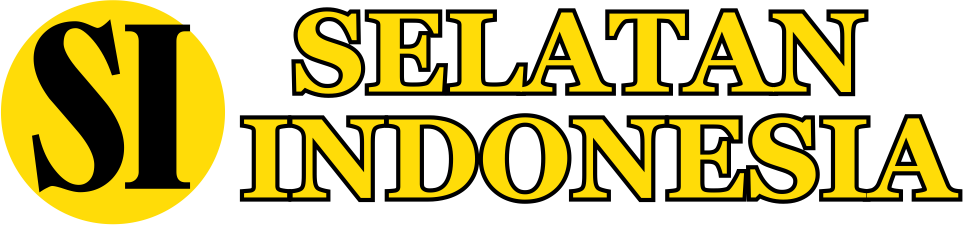











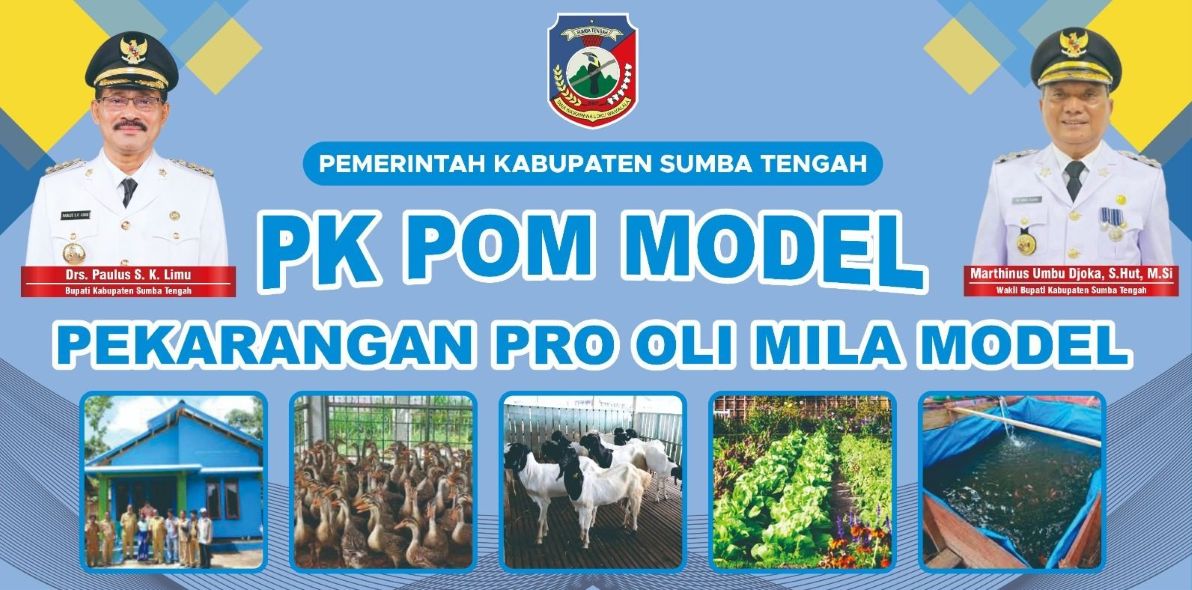





Komentar